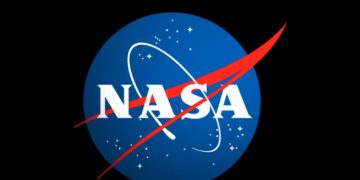*)CAHAYA PASUNDAN

Oleh: Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si (Ketua Bidang Agama Paguyuban Pasundan)
Bepergian dalam pustaka hukum Islam disebut dengan safar, dan orang yang melakukannya disebut musafir. Secara bahasa, safar bermakna membuka atau menyingkap. Sementara secara istilah, berarti keluar dari negeri atau daerah tempat bermukim menuju suatu tempat dengan jarak tempuh tertentu yang membolehkan seseorang untuk menggasar atau menjamak shalatnya.
Bepergian dinamai safar karena dapat menyingkap wajah dan akhlak asli musafir, karena saat safar itulah sifat-sifat asli seseorang akan terlihat (Lisin al-‘Arab 4/368).
Terkait dengan definisi safar tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jarak safar yang menjadikan shalat boleh diqashar. Ada tiga pendapat dalam hal ini:
1. Perjalanan disebut safar jika telah mencapai jarak 48 mil atau 85 km. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi’i, Hanbali dan Maliki. Dalil mereka adalah hadis berikut:
Dahulu Ibn “Umar dan Ibn “Abbas Ra mengqashar shalat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud (16 farsakh).” (Hr Al-Bukhari)
Namun, sebagian ulama menyanggah bahwa hadis tersebut bukan menunjukkan batasan jarak safar. Sehingga dibolehkan mengqashar shalat.
2. Perjalanan disebut safar jika ditempuh dengan berjalan kaki selama tiga hari tiga malam. Inilah pendapat ulama mazhab Hanafi. Dalil mereka adalah hadis dari Ibn “Umar, bahwa Nabi Saw bersabda:
“Janganlah seseorang bersafar selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.” (Hr Al-Bukhari)
Di samping itu, mereka juga berdalil dengan hadis dari ‘Ali Ra, yang berkata:
Rasulullah Saw menjadikan tiga hari tiga malam sebagai jangka waktu (mengusap khuf) bagi musafir, dan sehari semalam untuk yang mukim.” (Hr Muslim)
3. Tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama sudah bisa disebut safar, maka sudah boleh mengqashar shalat. Inilah pendapat Syaikhul-Islam Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan mazhab Zhahiri. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw pernah menempuh jarak kurang dari yang disebutkan tadi, dan beliau mengqashar shalat.
Dari Yahya bin Yazid al-Huna’i, ia berkata: Saya pernah bertanya pada Anas bin Malik mengenai qashar shalat. Anas menjawab, “Rasulullah Saw pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh Syu’bah ragu dalam penyebutan ini lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat (qashar shalat).” (Hr Muslim)
Ibn Hajar al-‘Asqalani berkata, “Itulah hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqashar shalat. Itulah hadis yang paling tegas.” (Fath al-Bari, 2: 567)
Jumhur (mayoritas) ulama menyanggah pendapat di atas, dan berkata bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi Saw mulai qashar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Dalil lain yang mendukung pendapat ketiga ini adalah hadis dari Anas bin Malik Ra berikut:
Dari Anas bin Malik Ra, ia berkata bahwa Nabi Saw pernah shalat di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah (sekarang: Bi’r ‘Ali) shalat dua rakaat. (Hr Al-Bukhari).
Padahal jarak antara Madinah dan Bi’r ‘Ali hanya sekitar tiga mil.
Sementara itu, Ibn Taimiyah berkata, “Nabi Saw sendiri tidak memberikan batasan jarak safar, dan tidak juga memberikan batasan waktu atau tempat. Berbagai pendapat dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Untuk menentukan batasan safar amatlah sulit karena bumi sendiri sulit diukur dengan ukuran jarak tertentu dalam kebanyakan safar. Pergerakan musafir pun berbeda-beda. Hendaklah kita tetap membawa makna mutlak sebagaimana disebutkan oleh syariat. Begitu pula, jika syariat mengaitkan dengan sesuatu, kita harus menetapkan demikian. Intinya, setiap musafir boleh mengqashar shalat di setiap keadaan yang disebut safar. Baginya tetap berlaku berbagai hukum safar, seperti mengqashar shalat, shalat di atas kendaraan, dan mengusap khuf.” (Majmu’ al-Fatawa, 24: 12-13).
Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ketiga. Selama suatu perjalanan disebut safar, baik menempuh jarak dekat maupun jauh, maka ketika itu shalat boleh diqashar. (Lihat Shahih Figh Sunnah, 1: 481). Jika sulit menentukan apakah suatu perjalanan masuk kategori safar atau tidak, maka pendapat mayoritas ulama bisa digunakan, yaitu menetapkan jarak 85 km. Ini berarti jika seseorang telah menempuh jarak 85 km dari batas kotanya, maka itu sudah disebut safar. (http://www.mahad-larafug. Com/5-adab-saat-bepergian-safar-perjalanan-anda-bernilai-ibadah/). Wallahu a’lam.
Kemudian para ulama membagi safar menurut jenisnya, yaitu seperti berikut:
- Safar haram, yaitu safar untuk tujuan yang diharamkan Allah atau Rasul-Nya Saw. Misalnya, safar untuk berdagang khamar (minuman keras) dan merampok.
- Safar wajib, misalnya safar untuk melaksanakan haji wajib dan berjihad.
- Safar sunnah, misalnya safar untuk melaksanakan umrah atau haji sunnah.
- Safar mubah, misalnya safar untuk rekreasi dan berdagang.
- Safar makruh, misalnya bepergian seorang diri pada malam hari Nabi Saw bersabda, “Seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada dalam kesendirian sebagaimana yang aku ketahui, tidak akan ada seorang pengendara pun yang berjalan sendirian pada waktu malam hari.” (Hr Al-Bukhari)
Ditinjau dari aspek hukum, safar terbagi tiga, yakni: (1) safar taat, (2) safar maksiat, dan (3) safar mubah. Safar taat adalah perjalanan yang dilakukan untuk menunaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, perjalanan haji, umrah, jihad, silaturahim, dan menjenguk orang sakit. Safar maksiat adalah perjalanan untuk melakukan sesuatu yang dilarang syariat, seperti untuk berbuat maksiat. Adapun safar mubah adalah perjalanan untuk melakukan aktivitas duniawi yang dihalalkan secara syariat, seperti untuk berdagang, rekreasi, dan berburu (https://almanhaj.or.id/-jenis-jenis-safar/.html). (*)