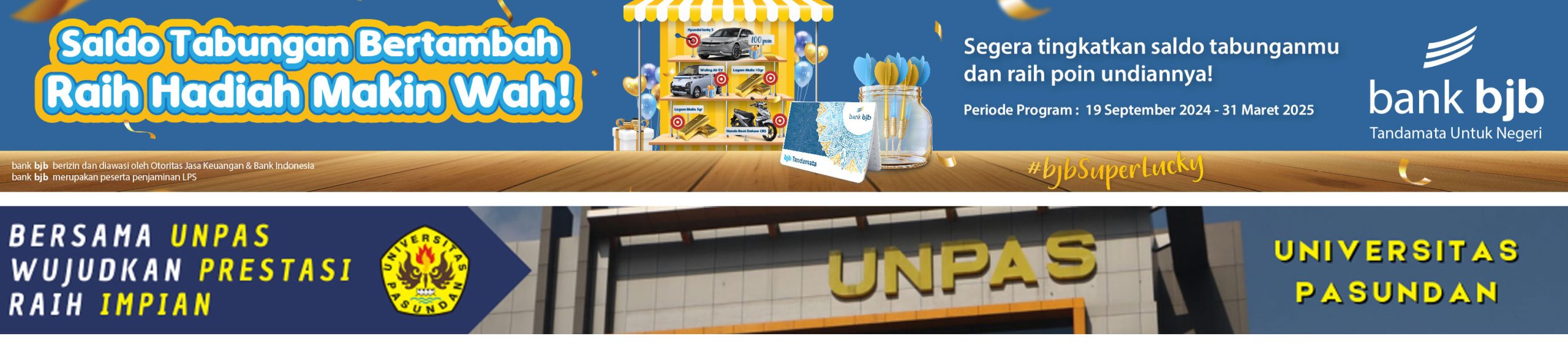Oleh: Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Pilkada Jakarta)
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ketika Pilkada Jakarta telah usai, pembicaraan publik tak hanya berputar pada siapa kandidat yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada, diskursus lain yang tak kalah penting justru mengemuka: fenomena golongan putih (golput). Dalam demokrasi elektoral, golput sering kali dianggap sebagai problem akut yang menggerus legitimasi pemilihan umum. Namun, di tengah derasnya upaya mendorong partisipasi politik, mengapa golput tetap menjadi “pemenang” yang tak terelakkan?
Pilkada Jakarta selalu menjadi barometer politik nasional. Sebagai episentrum kekuasaan, Jakarta tak hanya mencerminkan dinamika politik lokal, tetapi juga merefleksikan wajah demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Namun, kehadiran golput yang masif kerap menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini cerminan apatisme, ataukah sinyal adanya ketidakpuasan mendalam terhadap sistem yang berjalan?
Cerminan Kekecewaan
Fenomena golput bukanlah barang baru dalam politik Indonesia. Dalam setiap pemilu, baik nasional maupun daerah, golput selalu muncul sebagai aktor senyap yang menentukan peta akhir permainan politik. Dalam Pilkada 2012, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta hanya mencapai 63,62% pada putaran pertama, yang meningkat menjadi 66,71% pada putaran kedua. Namun, angka ini tetap menunjukkan bahwa lebih dari 30% warga memilih tidak menggunakan hak pilihnya.
Pada Pilkada 2017, partisipasi pemilih naik signifikan hingga 77%, yang menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI Jakarta. Namun, situasi ini tidak bertahan pada Pilkada 2024. Berdasarkan data dari Charta Politika, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 58%. Dengan kata lain, angka golput melonjak hingga 42%, tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta.
Golput dalam konteks ini sering kali menjadi representasi kekecewaan masyarakat terhadap kandidat yang bertarung. Dalam demokrasi yang ideal, pemilih dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mampu merepresentasikan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Namun, ketika kandidat yang tersedia dianggap sama-sama jauh dari harapan, sebagian masyarakat cenderung memilih untuk tidak memilih sama sekali.
Selain itu, golput juga menjadi kritik diam-diam terhadap sistem politik yang berjalan. Ketika demokrasi elektoral hanya berkutat pada perebutan kekuasaan tanpa disertai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan tergerus. Golput, dalam hal ini, menjadi bentuk perlawanan simbolis terhadap sistem yang dianggap gagal.
Politik Uang dan Kepercayaan
Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya angka golput adalah praktik politik uang yang terus menghantui setiap penyelenggaraan pemilu. Jakarta, sebagai kota metropolitan dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif tinggi, ironisnya tetap tak luput dari praktik semacam ini. Ketika proses politik didikte oleh uang, masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa pemilu adalah mekanisme yang adil untuk memilih pemimpin terbaik.
Politik uang bukan hanya menciderai integritas pemilu, tetapi juga memperkuat narasi bahwa politik adalah arena transaksional semata. Di satu sisi, kandidat dengan kekuatan finansial yang besar mendominasi panggung politik. Di sisi lain, pemilih yang pragmatis memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan jangka pendek. Akibatnya, golput menjadi pilihan rasional bagi mereka yang enggan terlibat dalam proses yang dianggap tidak bermoral.
Peran Media dan Polarisasi Politik
Fenomena golput juga tak lepas dari pengaruh media dan polarisasi politik yang kian tajam. Dalam Pilkada Jakarta, media sering kali menjadi aktor penting yang memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat. Sayangnya, alih-alih menjadi penyampai informasi yang objektif, media sering kali terseret dalam kepentingan politik tertentu.
Ketika media kehilangan independensinya, masyarakat cenderung bingung membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekadar propaganda. Dalam situasi seperti ini, golput muncul sebagai bentuk protes terhadap manipulasi informasi yang merusak kualitas demokrasi.
Selain itu, polarisasi politik yang tajam juga berkontribusi pada meningkatnya angka golput. Pilkada Jakarta beberapa kali menjadi arena konflik ideologis yang membelah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan. Bagi sebagian pemilih, keterbelahan ini menciptakan kelelahan politik yang membuat mereka enggan berpartisipasi.
Mencari Solusi
Mengurangi angka golput tidaklah mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat yaitu:
Pertama, pendidikan politik harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya partisipasi politik dalam membangun demokrasi yang sehat. Pendidikan politik tidak hanya bisa dilakukan melalui institusi formal, tetapi juga melalui kampanye yang kreatif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Kedua, reformasi sistem politik menjadi kunci. Partai politik harus mampu menawarkan kandidat yang berkualitas dan memiliki rekam jejak yang jelas. Dalam hal ini, proses seleksi calon pemimpin harus dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi, bukan sekadar karena faktor popularitas atau kedekatan dengan elit tertentu.
Ketiga, integritas penyelenggara pemilu harus dijaga. Bawaslu dan KPU memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Selain itu, pengawasan terhadap praktik politik uang harus diperketat agar masyarakat merasa bahwa suaranya benar-benar dihargai.
“Pemenang” yang Tidak Diinginkan
Pada akhirnya, golput bukanlah ancaman yang harus dimusuhi, melainkan sinyal yang perlu direspons dengan bijak. Dalam demokrasi, tidak memilih pun adalah pilihan yang sah dan harus dihormati. Namun, ketika golput menjadi pilihan mayoritas, ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam sistem yang kita bangun.
Pilkada Jakarta 2024 menjadi momentum untuk merefleksikan ulang arah demokrasi kita. Jangan sampai golput terus menjadi “pemenang” yang tidak diinginkan karena ketidakmampuan kita menyediakan proses politik yang lebih inklusif, adil, dan bermakna.
Masyarakat Jakarta, dengan segala keragamannya, layak mendapatkan pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan mereka. Dan tugas kita semua adalah memastikan bahwa pemilu, sebagai instrumen demokrasi, benar-benar mampu menjalankan fungsi tersebut. Golput bukanlah musuh; ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah demokrasi kita yang sebenarnya. (han)