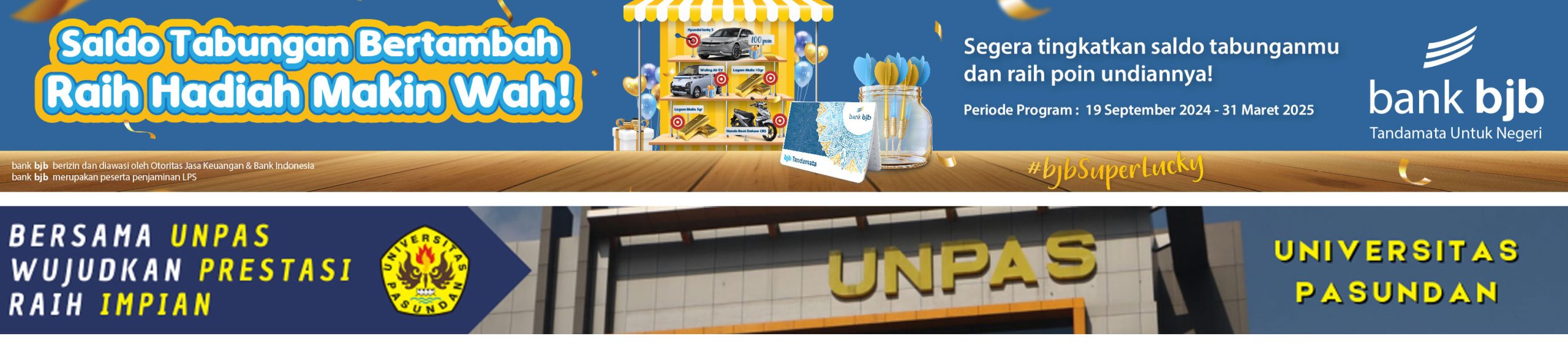Oleh: Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat (Partai Tanpa Partikelir)
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Politik selalu tentang orang. Tapi, apakah partai harus selalu menjadi milik seseorang?
Di Indonesia, partai sering kali terasa lebih seperti milik pribadi daripada milik publik. Ia lahir dari tangan seorang tokoh, berkembang dengan namanya, dan dalam banyak kasus, mati bersamanya. Sejarah partai kita adalah sejarah figur. Seolah-olah tanpa orang itu, partai kehilangan jiwa. Seperti rumah kosong yang tak lagi berpenghuni, tetapi tetap dipertahankan karena nama yang pernah melekat padanya.
Partai politik yang tumbuh dari seorang individu sering kali bukan partai dalam pengertian demokrasi yang sesungguhnya, melainkan partikelir politik—kendaraan pribadi yang dikemas sebagai institusi publik. Ketika seorang tokoh mendirikan partai, ia bukan hanya menciptakan struktur politik, tetapi juga membangun loyalitas personal. Para pengikutnya tidak sekadar menjadi kader, tetapi lebih seperti prajurit yang siap mempertahankan kepentingan pemimpinnya.
Tapi apa jadinya jika partai benar-benar menjadi partai—bukan sekadar kepanjangan tangan seseorang?
Partai dari Nama, Partai Tanpa Nama
Di banyak negara dengan demokrasi yang matang, partai politik lahir dari ideologi, bukan dari nama seseorang. Partai Buruh di Inggris, Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat, atau CDU di Jerman—semuanya memiliki karakter yang melekat pada nilai-nilai, bukan sekadar pada figur. Pemimpin datang dan pergi, tetapi partai tetap hidup.
Di Indonesia, fenomena ini jarang terjadi. Banyak partai terlahir bukan dari gagasan, melainkan dari kehadiran seseorang. Bung Karno dengan PNI, Mohammad Natsir dengan Masyumi, Megawati dengan PDI Perjuangan, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Demokrat hingga Prabowo dengan Gerindra. Nama-nama besar ini melekat begitu kuat pada partai yang mereka bangun, hingga sulit dibayangkan partai-partai itu tanpa mereka.
Ketergantungan pada figur ini membawa masalah serius. Partai tidak lebih dari instrumen kepentingan personal. Loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi. Kaderisasi mandek karena yang dicari bukan pemimpin baru, melainkan orang-orang yang cukup patuh untuk melestarikan pengaruh pemimpin lama.
Setiap kali seorang tokoh mulai melemah, partainya pun ikut gamang. Seperti rumah tanpa fondasi, ia mudah goyah diterpa perubahan zaman.
Politik dan Nama Keluarga
Max Weber pernah mengatakan bahwa kepemimpinan karismatik hanya bisa bertahan jika mampu bertransformasi menjadi kepemimpinan yang legal-rasional—kepemimpinan yang berbasis sistem, bukan individu. Tapi di Indonesia, transformasi ini jarang terjadi.
Sebagian besar partai lebih menyerupai kerajaan kecil. Pemimpin partai bukan hanya memegang kendali atas keputusan politik, tetapi juga memastikan bahwa tak ada yang bisa menggantikannya kecuali orang-orang terdekat.
Fenomena ini melahirkan politik dinasti, di mana partai bukan sekadar alat perjuangan politik, melainkan juga warisan keluarga. Kepemimpinan partai berjalan dalam garis darah. Bukan siapa yang paling kompeten, melainkan siapa yang paling dekat dengan pemilik partai.
Dalam sistem seperti ini, politik kehilangan daya hidupnya. Perdebatan tidak lagi ada, kritik dianggap pengkhianatan, dan partai hanya menjadi ruang eksekusi untuk kehendak segelintir orang.
Tapi demokrasi tidak bekerja seperti itu. Demokrasi bukan tentang siapa memiliki partai, tetapi bagaimana partai bisa menjadi milik semua.
Mungkinkah Partai Tanpa Partikelir?
Pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki partai tanpa partikelir—partai yang benar-benar menjadi institusi publik, bukan properti pribadi?
Secara teoretis, mungkin. Secara praktik, sulit.
Mengubah partai dari milik perseorangan menjadi institusi yang demokratis membutuhkan keberanian untuk membangun sistem, bukan sekadar membangun loyalitas. Itu berarti partai harus memiliki demokrasi internal yang sehat, di mana pemilihan pemimpin dilakukan dengan kompetisi terbuka, bukan aklamasi atas dasar kehendak pemilik partai.
Kaderisasi juga harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas. Tidak ada partai yang bertahan lama tanpa regenerasi. Pemimpin harus lahir dari proses yang sistematis, bukan dari perintah pemimpin lama.
Lebih dari itu, kebijakan partai harus berbasis visi, bukan personalisasi. Sebuah partai yang matang tidak boleh kehilangan arah hanya karena pemimpinnya berganti. Ia harus tetap memiliki sikap politik yang konsisten, bahkan ketika figur yang mendirikannya sudah tiada.
Tapi ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia. Politik kita masih berada dalam cengkeraman figur-figur besar. Selama kita masih melihat partai sebagai kendaraan individu, bukan sebagai institusi yang lebih besar dari individu itu sendiri, perubahan semacam ini hanya akan menjadi utopia.
Dari Partai ke Gerakan Politik
Mungkin inilah sebabnya mengapa kepercayaan publik terhadap partai semakin menurun. Banyak orang, terutama generasi muda, mulai meninggalkan partai dan beralih ke gerakan politik yang lebih fleksibel.
Di berbagai negara, gerakan politik sering kali lahir sebagai respons terhadap kegagalan partai dalam merespons perubahan zaman. Gerakan Occupy, MeToo, Fridays for Future, dan banyak gerakan politik lainnya tidak berbasis pada partai, tetapi pada gagasan yang lebih luas.
Indonesia pun mulai mengalami fenomena serupa. Orang lebih tertarik untuk bergerak dalam komunitas atau organisasi sosial ketimbang terlibat dalam partai yang kaku dan hierarkis. Ini adalah tanda bahwa partai tidak lagi menjadi satu-satunya alat perjuangan politik.
Tapi apakah ini berarti partai akan mati? Tidak juga. Partai tetap diperlukan, tetapi hanya jika ia mampu beradaptasi.
Partai yang Bisa Bertahan
Dalam politik, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Partai yang bisa bertahan adalah partai yang memahami bahwa demokrasi bukan tentang memelihara nama besar, tetapi tentang menciptakan ruang bagi ide dan perubahan.
Partai yang bisa bertahan bukanlah yang dikelola seperti perusahaan keluarga, melainkan yang memiliki sistem yang mampu melahirkan kepemimpinan baru tanpa rasa takut kehilangan identitas.
Jika tidak, partai-partai ini hanya akan menjadi fosil politik. Mereka mungkin masih ada secara formal, tetapi secara substantif, mereka sudah mati.
Dan mungkin itu memang tak terhindarkan.
Mungkin, partai tanpa partikelir hanyalah ilusi. Atau mungkin, kita hanya belum cukup berani untuk mencobanya. (han)