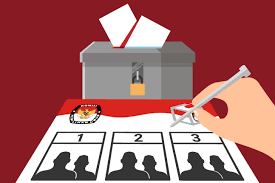Oleh: Firdaus Arifin, Dosen FH Unpas & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat (Makna Pemilu Setiap Lima Tahun Sekali)
WWW.PASJABAR.COM – Pemilu bukan sekadar pesta lima tahunan. Ia adalah mekanisme sirkulasi kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi. Namun, di tengah kompleksitas penyelenggaraan dan tarik-menarik kepentingan politik, tafsir terhadap makna konstitusional “pemilu setiap lima tahun sekali” sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 kini kembali menjadi sorotan.
Perdebatan ini menjadi relevan seiring Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menolak judicial review atas UU Pemilu dan UU Pilkada. Terkait keserentakan pemilu lima kotak. Tetapi membuka ruang tafsir konstitusional terhadap sistem dan jadwal penyelenggaraan pemilu ke depan.
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Jika dicermati secara gramatikal, frasa “setiap lima tahun sekali” menekankan pada periodisasi, bukan keserentakan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu.
Penyelenggaraan pemilu lima kotak—Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota—pada hari yang sama, bukan perintah konstitusi, melainkan pilihan desain institusional yang dibentuk oleh undang-undang.
Maka pertanyaan penting yang harus kita jawab: apakah pilihan model serentak lima kotak tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah digariskan UUD 1945?
Tafsir Konstitusi
UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa seluruh jenis pemilu harus dilaksanakan bersamaan. Yang diperintahkan adalah pemilu dilaksanakan dalam siklus lima tahun untuk menjaga keteraturan sirkulasi kekuasaan.
Dalam kerangka hukum tata negara, periodisasi ini mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, yakni keterbatasan masa jabatan melalui mekanisme pemilu reguler.
Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, memang memberikan enam alternatif model keserentakan pemilu. Tetapi tidak menyatakan bahwa pemilu lima kotak adalah satu-satunya model yang konstitusional.
Bahkan, MK menyarankan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan desain yang memudahkan pemilih, mengurangi beban penyelenggara, dan memperkuat sistem presidensial serta pelembagaan partai politik.
Jika kita kembali kepada asas dalam Pasal 22E ayat (1)—langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—maka yang menjadi batu ujinya bukan hanya “lima tahun sekali”, melainkan bagaimana asas-asas tersebut dapat dijalankan secara substantif.
Apakah pemilu lima kotak telah mampu menjamin keadilan pemilu? Apakah ia memperkuat sistem kepartaian dan kualitas representasi? Atau justru menghasilkan kelelahan demokrasi dan pelemahan institusional?
Beban Sistemik
Pemilu serentak lima kotak, sebagaimana dilaksanakan pada 2019 dan 2024, telah menghadirkan beban manajerial yang luar biasa. Beban teknis, administratif, dan fisik tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara, tetapi juga pemilih.
Tingginya angka suara tidak sah, kematian ratusan petugas KPPS, serta kebingungan dalam menentukan pilihan politik menjadi indikator bahwa sistem ini secara praktik telah menyulitkan pelaksanaan asas pemilu yang dijamin konstitusi.
Apakah dalam kondisi seperti itu kita bisa tetap mengatakan bahwa pemilu telah dilaksanakan secara “jujur dan adil”? Bukankah asas-asas tersebut tidak cukup hanya dinilai dari prosedur formal, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya?
Dalam kerangka teori hukum tata negara, “konstitusionalitas formal” harus dibaca berdampingan dengan “konstitusionalitas substantif”. Pemilu yang secara hukum terjadi setiap lima tahun, tetapi merusak substansi kedaulatan rakyat, sesungguhnya menjauh dari semangat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”
Kepentingan Pembentuk Undang-Undang
Sayangnya, seperti ditunjukkan dalam permohonan uji materi Perludem, pembentuk undang-undang cenderung mempertahankan status quo karena adanya konflik kepentingan elektoral. Para legislator adalah peserta pemilu itu sendiri. Maka, desain sistem pemilu lebih sering diatur bukan demi kebaikan demokrasi, melainkan demi elektabilitas.
Alih-alih mengevaluasi kerumitan dan dampak negatif pemilu lima kotak, DPR dan pemerintah justru membiarkannya berlangsung. Mahkamah Konstitusi pun tidak menggunakan momentumnya untuk menyatakan sistem tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ini yang menyebabkan siklus lima tahunan pemilu kehilangan substansi konstitusionalnya.
Dibutuhkan keberanian politik dan kebijaksanaan konstitusional untuk menempatkan asas pemilu sebagai landasan utama reformulasi sistem pemilu kita. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran bahwa “serentak adalah ideal”, padahal di balik itu menyimpan banyak mudarat.
Format Baru: Dua Klaster
Dalam permohonannya, Perludem menawarkan alternatif yang layak dipertimbangkan secara serius, yaitu pemilu serentak dalam dua klaster: pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional meliputi pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Sementara dua tahun setelahnya, dilakukan pemilu serentak daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD.
Model ini menjaga periodisasi lima tahun sekali, sekaligus memberikan ruang konsolidasi bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih. Beban kerja tersebar, pendidikan politik lebih fokus, dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu menjadi lebih terukur. Ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menekankan keterwakilan dan integritas pemilu, bukan hanya kepatuhan pada hitungan waktu lima tahunan.
Transisi Konstitusional
Tentu, perubahan model ini akan menimbulkan implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik hasil pemilu 2024. Namun dalam hukum tata negara, masa transisi konstitusional adalah hal yang lazim.
Kita pernah memangkas masa jabatan anggota DPR hasil Pemilu 1997 akibat reformasi. Maka, memperpanjang atau menyesuaikan masa jabatan anggota DPRD atau kepala daerah untuk menyelaraskan format keserentakan yang baru, adalah pilihan yang sah dan konstitusional.
Prinsipnya adalah: perubahan dilakukan demi memperbaiki kualitas demokrasi, bukan untuk memperpanjang kekuasaan semata. Oleh sebab itu, jika desain baru ini diterapkan, harus dipastikan bersifat satu kali transisi dan diawasi secara ketat dalam proses legislasi.
Menjaga Ruh Konstitusi
Pemilu setiap lima tahun sekali adalah prinsip penting dalam demokrasi. Namun ia tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai hanya soal kalender. Ia adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat, integritas lembaga perwakilan, dan legitimasi pemerintahan.
Bila desain pelaksanaannya justru menghambat keterwakilan yang bermakna, maka sesungguhnya kita telah mengkhianati semangat konstitusi.
Sudah saatnya Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden membuka kembali ruang diskusi publik tentang sistem pemilu. Penataan ulang keserentakan bukan sekadar teknis, melainkan koreksi atas penyimpangan makna “lima tahun” yang selama ini disalahpahami.
Demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari keberlangsungan pemilu, tetapi dari bagaimana pemilu itu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.
Jika kelima kotak itu terlalu berat untuk ditanggung oleh satu hari dan satu tangan, maka janganlah dipaksakan atas nama konstitusi yang justru tidak pernah memerintahkannya. (han)