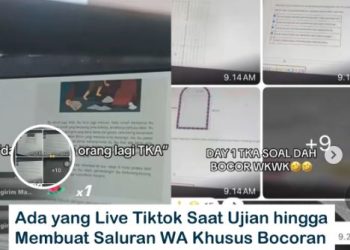Oleh: Firdaus Arifin, Dosen FH Unpas & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat (Ketika Pintar Tak Berarti Bijak)
WWW.PASJABAR.COM – Ada yang membanggakan gelar, ada yang menumpuk buku, ada yang merayakan angka-angka cemerlang di atas kertas ujian. Mereka dipanggil “orang pintar.” Tetapi tak jarang, ketika persoalan hidup mengetuk pintu—perselisihan di meja makan, konflik di dunia kerja, keputusan dalam ruang publik—kepintaran itu luruh. Yang tersisa hanya wajah kebingungan, kadang bahkan kesombongan.
Seperti Socrates yang pernah berkata, “Aku tahu bahwa aku tidak tahu.” (Apology, Plato). Kalimat itu seakan menegaskan: pengetahuan tidak selalu beriring dengan kebijaksanaan. Ada jurang antara knowing dan understanding, antara menghafal konsep dan menghayati makna.
Kita sering menyaksikan, orang yang fasih mengutip teori, pandai berhitung dengan logika, justru gagal menemukan jalan keluar yang sederhana. Mereka pandai memetakan masalah, tapi tidak mampu berjalan di jalan berdebu yang harus dilalui.
Logika
Mungkin sebabnya, logika yang terlalu tajam bisa melukai diri sendiri. Seperti pedang bermata dua, ilmu pengetahuan bisa memotong masalah, tapi juga bisa mengiris habis kebijaksanaan.
Kita pernah melihat, para ekonom dengan teori pertumbuhan dan angka statistik bicara di forum, tetapi lupa menyapa wajah-wajah lapar di gang sempit. Para pejabat dengan ijazah panjang berbicara tentang “good governance,” tapi tersandung di trotoar kecil korupsi receh. Para sarjana hukum fasih berdebat soal pasal, namun tak bisa menengahi konflik dua tetangga yang berebut pagar.
Ada paradoks di sini: semakin pintar seseorang dalam rumus dan definisi, semakin sering ia kehilangan kepekaan pada hal-hal kecil yang justru menentukan hidup bersama.
Kebijaksanaan
Bijak berbeda dari pintar. Bijak lahir dari perjumpaan, bukan sekadar pembacaan. Ia tumbuh dari luka, dari empati, dari pengalaman gagal. Seorang petani yang tak pernah kuliah bisa lebih bijak menimbang musim daripada sarjana pertanian yang hafal teori iklim. Seorang ibu bisa lebih bijak membaca hati anaknya daripada psikolog yang sibuk dengan skala tes.
Kebijaksanaan adalah kemampuan menempatkan diri, memilih waktu, mengenali keterbatasan, dan menerima bahwa tak semua persoalan bisa dijawab dengan kepintaran.
Orang pintar sering ingin menang. Orang bijak rela mengalah agar persoalan selesai. Orang pintar sibuk menjelaskan. Orang bijak memilih mendengar. Orang pintar berdebat. Orang bijak merangkul.
Arogansi
Bahaya terbesar dari kepintaran adalah kesombongan. “Aku tahu,” katanya. “Aku menguasai.” Lalu ia menutup telinga bagi kemungkinan lain. Dari situlah lahir kebodohan baru: kebodohan yang dibungkus pengetahuan.
Kita melihatnya di ruang politik, ketika elite merasa paling mengerti tentang rakyat, padahal tak pernah duduk di warung kopi kampung. Kita melihatnya di ruang birokrasi, ketika pejabat sibuk dengan presentasi berlapis data, tapi lupa turun ke pasar melihat harga cabai. Kita melihatnya di kampus, ketika akademisi mengutip filsuf asing, tapi tak peka pada derita mahasiswa yang tak mampu bayar UKT.
Pintar yang arogan tak ubahnya lampu terang benderang, tapi membutakan mata.
Kesederhanaan
Kebijaksanaan sering kali lahir dari kesederhanaan. Dari orang tua yang memilih diam ketika anaknya berontak, bukan karena kalah argumen, melainkan karena tahu bahwa cinta lebih penting daripada benar. Dari seorang pemimpin desa yang membiarkan warganya bicara panjang lebar, lalu menyimpulkan dengan satu kalimat yang menyejukkan. Dari sahabat yang lebih memilih hadir di samping, tanpa nasihat panjang, karena tahu kehadiran lebih berharga dari petuah.
Dalam kesederhanaan itu ada ruang bagi manusia untuk merasa dipahami. Dan di situlah masalah sering menemukan jalan keluar.
Sejarah
Sejarah pun menyodorkan cermin. Romawi yang megah runtuh bukan karena bodoh, melainkan karena terlalu percaya diri pada strategi militernya. Uni Soviet bubar meski maju dalam sains, tapi gagal memahami denyut rakyatnya. Jepang sebelum Perang Dunia II tumbuh dalam intelektualisme yang dingin, namun lupa bahwa kesombongan justru bisa menyeret pada kehancuran.
Itu semua bukan kutipan, melainkan refleksi dari perjalanan sejarah: bahwa kepintaran tak menjamin keberlanjutan, bila tak disertai kebijaksanaan.
Pendidikan
Di sinilah letak masalah pendidikan kita: terlalu lama menjadikan sekolah sebagai pabrik kepintaran, bukan ruang pembelajaran kebijaksanaan. Kita menilai anak dari angka rapor, bukan dari kemampuan mereka mendengar dan memahami. Kita bangga dengan ranking, tapi tak pernah menanyakan apakah mereka bisa berbelas kasih.
Kita membiarkan generasi tumbuh dengan logika yang rapi, tapi hati yang kering. Seolah-olah dunia ini hanya deretan soal ujian, bukan pergulatan nilai.
Refleksi
Mungkin saatnya kita mengubah ukuran keberhasilan. Tidak lagi semata berapa banyak ilmu yang dikumpulkan, tapi seberapa dalam ia dihidupi. Tidak lagi berapa panjang daftar gelar, tapi seberapa nyata jejak yang ditinggalkan.
Pintar hanyalah tangga. Bijak adalah tujuan. Pintar adalah jalan masuk. Bijak adalah rumah.
Dan rumah itu hanya bisa dibangun dengan kerendahan hati.
Goethe pernah menulis: “Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” Mengetahui tidak cukup, harus diaplikasikan. Mau saja tidak cukup, harus dilakukan.
Kita boleh saja merayakan kepintaran, tapi jangan lupa, kepintaran tanpa kebijaksanaan bisa menjelma bencana. Seperti kapal besar dengan mesin canggih tapi tanpa kompas: cepat, kuat, namun tersesat.
Mungkin, di tengah hiruk pikuk zaman yang semakin memuja gelar dan teknologi, kita perlu kembali mengingat hal yang paling sederhana: bahwa bijak tidak selalu lahir dari pintar, tetapi dari kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan, mendengar orang lain, dan mencintai kehidupan.
Karena pada akhirnya, orang pintar bisa membuat dunia berputar lebih cepat, tetapi hanya orang bijak yang bisa membuat dunia layak untuk dihuni. (han)